Tere Liye menuai kritik. Berawal dari status berikut ini:
Indonesia itu merdeka, karena jasa-jasa tiada tara para pahlawan- yang sebagian besar diantara mereka adalah ulama-ulama besar, juga tokoh-tokoh agama lain. Orang-orang religious beragama.
Apakah ada orang komunis, pemikir sosialis, aktivis HAM, pendukung liberal, yang pernah bertarung hidup mati melawan serdadu Belanda, Inggris atau Jepang? Silahkan cari.
Anak muda, bacalah sejarah bangsa ini dengan baik. Jangan terlalu terpesona dengan paham-paham luar, seolah itu keren sekali; sementara sejarah dan kearifan bangsa sendiri dilupakan.
Saya pribadi mencoba menelusuri sebetulnya pandangan Tere Liye terhadap komunisme-sosialisme-HAM-liberalisme.
Awal tahun ini, Kompas mengunggah berita dengan judul Hari Ini 39 Tahun Lalu, Lebih Dari 1,2 Juta Rakyat Kamboja Tewas. Kutipan berita, “KOMPAS.com – Sejak tentara Khmer Merah komunis mengambil alih kekuasaan dalam bulan April 1975, lebih dari satu juta rakyat Kamboja mati karena kelaparan, menderita sakit, atau ditembak mati. Angka ini berdasar laporan majalah dua redaktur senior Readers Digest yang mewawancarai lebih dari 300 orang. Dari wawancara tersebut ditarik kesimpulan lebih dari 1,2 juta warga Kamboja tewas. Para pengungsi yang diwawancara menceritakan bahwa perintah penembakan diberikan
untuk semua orang yang pernah bekerja bagi rezim Lon Nol,” (Kompas, 26 Januari 2016).
Tere Liye menulis tanggapan atas berita tersebut:
Itu judul dari berita KOMPAS. Salah-satu media penting dan berpengaruh di Indonesia, yang jelas lebih santun dibanding media-media lain, salah-satu media dengan akurasi tinggi. Tapi kenapa mereka menggunakan judul yang seolah “sangat provokatif”?
Tidak. Itu bukan provokasi. Itu adalah fakta. Maka mau dikasih judul bagaimanapun, dibuat sehalus apapun, tetap saja berita ini memang faktanya begitu: 39 tahun lalu, lebih dari 1,2 juta rakyat Kamboja tewas oleh kekejaman pasukan Khmer Merah. Kelompok KOMUNIS, yang berusaha mengangkangi seluruh negeri, mengambil kekuasaan dari pemerintah di bulan April 1975. Sebagian dari rakyat Kamboja mati karena kelaparan, menderita sakit dalam kecamuk perang yang disebabkan pasukan Khmer Merah, dan tidak sedikit yang tewas karena disiksa, ditembak mati, terserah apa maunya si komunis.
Kejam sekali. Cukup alasan sepele saja bagi pasukan Khmer Merah menghabisi orang sekampung. Angkat senjata, tembak, habisi.
Sepuluh tahun sebelumnya, di Indonesia, partai komunis (PKI) juga melakukan hal yang sama, mereka berusaha mengambil-alih kekuasaan, menewaskan jenderal-jenderal, membunuh rakyat banyak, tambahkan: menipu orang2 polos agar bergabung, atau seolah menjadi bagian mereka, untuk kemudian orang2 yang tidak berdosa ini menjadi terjepit dalam pertikaian dan masalah serius dengan TNI dan pemerintah. Buanyak sekali korban keganasan PKI di pelosok negeri ini.
Nah, yang menarik sekarang, apakah di Kamboja, sisa-sisa komunis pelaku kekejaman ini berusaha menyangkal tragedi tersebut? Apakah mereka juga akan memutarbalikkan fakta, bahwa bajingan pemerintahlah yang salah, bedebah tentara resmilah yang dusta, pun rakyat sialan lain yang tidak sependapat dengan mereka yang culas? Apakah mereka akan membuat film2, buku2, tulisan2, bahwa Khmer Merah-lah yang jadi korban, merekalah yang dibantai habis2an? Apakah keturunan komunis Khmer Merah akan berlagak sekali berusaha meneruskan ideologi orang tua mereka dulu, mulai membanjiri media sosial dengan propaganda komunisnya? Atau cucu, keturunan pasukan Khmer Merah menuntut pemerintah Kamboja sekarang minta maaf dengan mereka?
Menarik bukan? Silahkan dicari tahu sendiri, kemudian dipikirkan dalam-dalam kelakuan fans komunis di seluruh dunia.
Catat ini baik-baik, buat siapapun yang ingin bersilat lidah atas kekejaman komunis, ketahuilah, di dunia ini, berserakan bukti, berjuta orang mati, di berbagai negara, akibat bengis dan ambisiusnya kelompok komunis berkuasa. Kalian bisa membuat orang banyak melupakannya lewat propaganda baru, tapi tidak kepada sebagian orang. Tidak kepada orang2 yang menyaksikan kekejaman itu, yang masih menyentuh sisa-sisa kesedihan di keluarganya, yang terus mewarisi catatan-catatan penuh tangis dan darah, karena kejamnya kalian komunis. Tidak akan pernah.”
Hari ini Bang Tere menulis:
Saya mulai menulis di koran-koran sejak SMA, saat kuliah, masuk kampus perubahan, yangdipenuhi banyak aktivis kelas berat (baiklah, akan saya sebut saja, kuliah di UI), saya menemukan banyak pemikiran2 baru yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Juga buku2 yang tidak pernah saya baca sebelumnya.
Sepertinya keren sekali menjadi aktivis, yang jago bicara tentang Marxisme, lihai berdebat soal paham sosialis, kemudian meletakkan foto Che Guevara, atau tokoh2 yang nampak gagah sebagai “pemberontak”, “perlawanan”, “pejuang”, dsbgnya sebagai idola. Untuk kemudian, di selasar2 kampus, di basecamp organisasi, di kostan, di forum2, berbincang panjang tentang paham-paham ini, berdebat tidak ada habisnya.
Waktu terus berjalan, kehidupan kampus terus bergerak, untuk kemudian muncul lagi jenis aktivis baru, pergerakan yang berbeda. Yang kali ini bicara tentang kesetaraan, hak asasi, kebebasan bicara, liberal, demokrasi, dan semua jargon2 tidak kalah hebatnya. Seperti terlihat hebat benar kalau sudah bicara tentang ini di seminar2, celoteh saat di angkutan umum, atau saat mengirim SMS, ow, saya lupa, dulu HP masih langka, lebih banyak pager. Itu bukan “pagar”, dek, tapi pager, radio panggil. Kecil bentuknya, bisa menerima pesan, “Kawan, ada diskusi tentang HAM di markas pukul 13.00.”
Itu masa-masa yang dipenuhi hal baru, euforia tidak terkira–karena saya datang dari pelosok kampung. Apapun ingin dicoba. Di kampus ada kegiatan apalah, ikut. Teman2 ngajak ini, itu, ikut. Dan bukan hanya yang beginian saja, saya juga menyemplungkan diri ikut Jamaah Tablig, alias JT, juga bersinggungan dengan kegiatan dan aktivis seperti HMI, PMII, dsbgnya, dsbgnya.
Bahkan termasuk ada yang ngajak aktivitas menghitung burung di Gunung Salak, saya ikut. Menghitung ikan di lautan, juga ikut. Kecuali yang sejenis NII, saya tidak ikutan, nasib menyelamatkan saya, atau boleh jadi mereka tidak tertarik menjadikan saya kader–”ah, anak ini tidak menjanjikan, cuma ikutan nyari konsumsi gratis saja.”
Dengan begitu banyak paham tersebut, lantas mana yang memang brilian dan paling keren?
Jawabannya: tidak ada.
Jawabannya: tidak ada.
Saya memutuskan untuk berhenti terlalu mengagung-agungkan paham-paham tersebut. Mengotot sekali merasa itu sesuatu yang paling keren. Tidak lagi. Lebih baik saya kembali ke masa silam, saat masa kanak-kanak saya dibesarkan di pelosok. Guru2 mengaji, guru2 di sekolah. Orang tua bersahaja di sekitar kita. Kearifan lokal, kearifan bangsa sejak lama, yang jelas adalah turunan dari nasehat agama yang baik.
Dunia ini semakin modern, orang2 punya paham yang semakin mutakhir, misalnya: freedom of speech. Apakah memang begitu realitasnya? Tidak. Dunia ini semakin tenggelam dalam hipokrasi, kemunafikan. Jangankan menegakkan freedom of speech, kita bahkan sudah sejak awal sudah terkotak2 ruang diskriminasi. Dan tentang paham2 yg saya baca hebat sekali ketika kuliah dulu? Juga omong kosong saja. Kalian tahu? Negara paling demokratis di dunia ini, justeru yang paling banyak menembakan rudal. Negara paling sosialis, juga negara2 yang justeru miskin dan terbelakang, menyiksa rakyatnya. Sementara di media sosial, para penganut berbagai paham terus bertengkar, berdebat tidak habis-habisnya.
Maka biarlah hingar-bingar itu. Saya memutuskan untuk kembali ke guru-guru mengaji di kampung dulu. Saat kesederhanaan hidup terlihat sangat kongkret dan nyata. Saat menulis novel RINDU misalnya, itu salah-satu momen ketika saya kembali ke masa lalu. Ketika ulama diingat kembali sebagai bagian penting dalam perjuangan bangsa untuk merdeka–meskipun anak cucunya lebih sibuk bicara tentang hal hebat yang tidak nyambung lagi.
Saya tidak tahu sejauh mana perjalanan hidup kalian, entah kalian kuliah di negeri2 jauh, bertemu dengan orang2 baru, pemahaman2 baru, tapi ketahuilah, mau sejauh mana kaki kalian melangkah, hidup ini tidak pernah bicara soal jargon. Hidup ini bicara tentang kebermanfaatan dan ahklak yang baik. Hanya itu.
***
Menurut pendapat saya pribadi, Tere Liye ada salahnya, dan ada benarnya. Kesalahan pertama Tere Liye adalah menganggap bahwa jika seseorang menjadikan Islam sebagai agama, maka otomatis ia akan menolak paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Faktanya tidak demikian. Banyak di antara tokoh nasional yang muslim tetapi sosialis secara ideologi. Misalnya, Tan Malaka, Presiden Sukarno, Muhammad Hatta, Sutan Syahrir, HOS Cokroaminoto, KH Agus Salim, KH Ahmad Dahlan, dan Ciptomangunkusumo (Jawablah Tere Liye, Kawan-kawan!, Lilik Krismantoro, 1/3/2016).
Hingga hari ini pun kita menjumpai banyak muslim yang Islam ‘secara status di KTP’, namun kapitalisme secara ideologi. Penarikan kesimpulan yang terlalu sederhana ini saya pandang sebagai kesalahan Tere Liye yang pertama. Kedua, Tere Liye seolah menganggap tidak ada pengemban sosialisme-komunisme-HAM-liberalisme yang berjuang melawan penjajahan. Padahal hingga hari ini pun, orang melawan penjajahan dengan alasan berbeda-beda.
Saya pribadi berpikir, Cut Nya’ Dien, Teuku Umar, Pangeran Diponegoro, hingga Bung Tomo; tentu tidak melawan penjajahan Belanda atas nama HAM. Semangat jihadlah yang mengantar mereka berjuang hingga titik darah penghabisan. Ini tentu semangat antipenjajahan berbeda dengan yang diusung oleh para pejuang demokrasi dan HAM. Sama-sama antipenjajahan Belanda, tetapi alasannya berbeda.
Hingga hari ini pun kita menjumpai, banyak aktivis muslim yang antipenjajahan Israel terhadap Palestina dengan alasan berbeda-beda. Sebagian besar muslim melawan dengan alasan demokrasi, dan pendudukan Israel atas Palestina tidak sesuai dengan HAM. Solusinya, mereka terus berharap bahwa Palestina bisa merdeka, lewat jalur diplomasi, melalui campur tangan Barat yakni PBB.
Minoritas muslim menolak penjajahan Israel atas Palestina bukan dengan alasan demokrasi dan HAM, melainkan karena itu bertentangan dengan Islam. Solusi yang ditawarkan adalah berhenti berharap Barat akan membantu memerdekakan Palestina, sekaligus mengajak ummat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan khilafah Islamiyah untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel.
Kekhilafan Tere Liye yang kedua, menurut saya adalah karena Tere Liye nampaknya belum bisa memahami hakikat ideologi dan pemikiran-pemikiran yang menjadi derivatnya. Kelemahan ini sejatinya menurut saya yang paling fatal, karena secara langsung Tere Liye nampaknya memahami Islam baru sebatas kebermanfaatan dan akhlak yang baik. Well, saya hampir 10 tahun tinggal di Barat; pernah di Amerika Serikat dan sekarang di Inggris. Kalau standarnya adalah ‘hawa nafsu saya sebagai manusia’, maka saya berani bersumpah bahwa negara-negara Barat yang maju jauh *lebih Islami* daripada negei-negeri Islam itu sendiri (jadi inget mau nulis soal paper penelitian How Islamic Are Islamic Countries?)
Selebihnya, saya menangkap semangat Tere Liye untuk kembali kepada Islam saja. Islam; tanpa komunisme-tanpa sosialisme-tanpa HAM-tanpa liberalisme-tanpa Marxisme-tanpa ide kesetaraan-tanpa ide freedom of speech-tanpa demokrasi.
Di poin ini saya sependapat dengan beliau. Menurut saya beliau sudah benar. Islam sudah sempurna tanpa memerlukan pemikiran-pemikiran tersebut. Catatan ini dibuat terutama untuk diri sendiri, agar bisa mengambil pelajaran dari keplesetnya Tere Liye dalam merangkai kata, sekaligus reminder untuk lebih serius mengaji Islam.
Bang Tere Liye, mungkin sudah waktunya Anda mengkaji (dan bukan sekadar membaca) kitab Nizham Al Islam.
Nurisma Fira,
Colchester, 1 Maret 2016

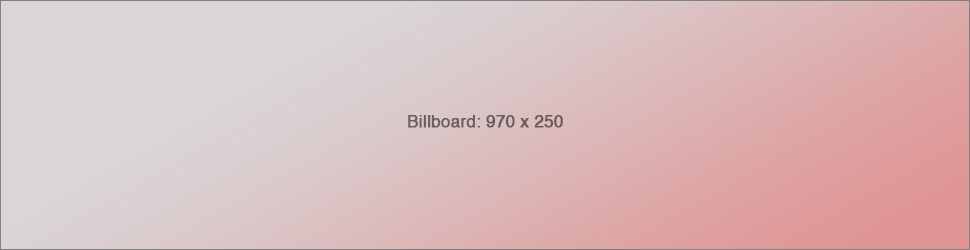
 Komentar
Komentar


